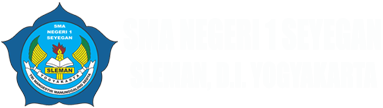Sejarah berdirinya Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (Yogyakarta) dan Kasunanan Surakarta Hadiningrat (Surakarta/Solo) merupakan kisah monumental tentang keruntuhan sebuah kerajaan besar di Jawa, yaitu Mataram Islam, akibat intrik internal dan politik adu domba kolonial VOC. Peristiwa perpecahan ini, yang dikenal sebagai Palihan Nagari (Pembagian Negara), diabadikan dalam dua perjanjian penting: Perjanjian Giyanti dan Perjanjian Salatiga.
Kemunduran Mataram Islam dan Konflik Internal
Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo (1613–1645). Namun, setelah wafatnya Sultan Agung, pengaruh Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) Belanda mulai menguat, seringkali campur tangan dalam urusan takhta.
Konflik internal besar muncul di kalangan keturunan Amangkurat IV (1719–1726), melibatkan tiga tokoh utama:
- Susuhunan Pakubuwana II: Raja Mataram yang memimpin pemindahan ibu kota dari Kartasura ke Surakarta pada tahun 1745 setelah keraton lama hancur akibat pemberontakan Mas Garendi (Sunan Kuning).
- Pangeran Mangkubumi: Adik kandung Pakubuwana II.
- Raden Mas Said (Pangeran Sambernyawa): Keponakan Pakubuwana II, yang menuntut hak atas takhta Mataram.
Pakubuwana II yang condong pada VOC membuat Mangkubumi dan Raden Mas Said bersekutu melancarkan perlawanan. Ketika Pakubuwana II wafat pada tahun 1749, konflik memuncak dan VOC mengangkat putranya, Pakubuwana III, sebagai raja Mataram, yang semakin menyulut kemarahan Mangkubumi.
Perjanjian Giyanti (1755): Lahirnya Dua Kesultanan
Untuk meredam peperangan yang berkepanjangan, VOC menjalankan siasat politik devide et impera (pecah belah). Setelah berhasil memisahkan Pangeran Mangkubumi dari Raden Mas Said, VOC menawarkan perundingan damai.
Perjanjian Giyanti ditandatangani pada 13 Februari 1755 di Desa Giyanti (kini Karanganyar, Jawa Tengah). Isi perjanjian ini secara resmi membagi Kerajaan Mataram Islam menjadi dua kekuasaan utama:
Pangeran Mangkubumi kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai raja dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwana I dan mendirikan keraton baru di Yogyakarta pada 1756. Perjanjian ini secara de jure mengakhiri riwayat Mataram Islam sebagai kerajaan tunggal.
Perjanjian Salatiga (1757): Pecahan Keempat
Pembagian kekuasaan tidak berhenti di Giyanti. Raden Mas Said, yang terus berjuang, baru dapat dihentikan dua tahun kemudian.
Perjanjian Salatiga ditandatangani pada 17 Maret 1757, melibatkan VOC, Pakubuwana III, Hamengkubuwana I, dan Raden Mas Said. Perjanjian ini memberikan Raden Mas Said sebagian wilayah Kasunanan Surakarta, yang kemudian mendirikan Kadipaten Mangkunegaran. Raden Mas Said diangkat sebagai Adipati Mangkunegara I dengan status setingkat raja (Pangeran Miji).
Bertahun-tahun kemudian, pada 1813, Inggris (yang sempat menggantikan VOC) juga mendirikan pecahan keempat, Kadipaten Pakualaman di Yogyakarta, yang dipimpin oleh Pangeran Natakusuma (Pakualam I). Dengan demikian, bekas Mataram terpecah menjadi empat pusat kekuasaan (disebut Vorstenlanden): Surakarta, Yogyakarta, Mangkunegaran, dan Pakualaman.
Warisan Budaya yang Berbeda
Pasca-Giyanti dan Salatiga, Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta mengembangkan ciri khas budayanya masing-masing.
- Yogyakarta cenderung mempertahankan tradisi dan arsitektur Jawa Hindu-Klasik yang kental.
- Surakarta menunjukkan pengaruh arsitektur dan budaya percampuran Jawa-Eropa, ditandai dengan nuansa bangunan yang sering berwarna putih-biru.
Hingga kini, Kesultanan Yogyakarta (bersama Pakualaman) menjadi Daerah Istimewa yang memiliki otonomi khusus, sementara Kasunanan Surakarta (bersama Mangkunegaran) tetap menjadi pusat pelestarian budaya Jawa yang dihormati di Indonesia.